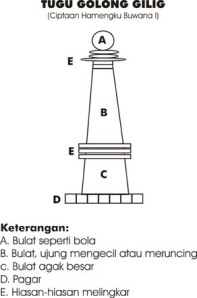Gunungkidul-JCM&matarama. Manthous telah meninggal dunia pada pukul 06.30 wib di Jakarta dan
jenazah akan dikebumikan hari ini tgl 9 Maret 2012 setelah sholat Jumat
di Playen Gunungkidul Yogyakarta.
Mungkin belum banyak yang mengenal sosok Manthous. Laki-laki
kelahiran Yogyakarta, 10 April 1950 ini adalah pendiri Campur Sari
sekaligus pencipta lagu. Nama Manthous cukup tersohor pada era tahun
1990-an, berkat lagu ciptaannya yang berjudul Getuk. Namun saat berada
di puncak kesuksesan, ia mengalami sakit stroke yang menyerangnya dari
tahun 2002 silam. Tanpa asuransi yang dimilikinya, kini Manthous hanya
menggantungkan hidup dari uang tabungannya. Bagaimana kisahnya?
Siang itu, Senin (7/3), suasana di Perumahan Bukit Pamulang, Ciputat,
terlihat lengang. Begitupun dengan suasana rumah milik sang maestro
Campur Sari, Manthous (60). “Mari masuk, Mas Manthous sudah menunggu di
dalam,” ujar perempuan bernama Utasih (55) yang tak lain adalah istri
dari Manthous. Dengan ramah Utasih langsung mempersilahkan masuk ke
dalam ruang tamu rumahnya yang memiliki ukuran 3×4 meter persegi.
Di ruang tamu terdapat sofa berwarna hijau muda bermotif bunga yang
terlihat sudah agak lusuh, serta sebuah meja terbuat dari kaca. Di atas
sofa tersebut Manthous terbaring lemah tak berdaya, akibat sakit stroke
yang dialaminya sejak tahun 2002. “Anda siapa?” tanya Manthous dengan
bicara agak terbata-bata.
Dengan mengenakan kemeja garis-garis berwarna cokelat dan memakai
kain sarung berwarna biru, Manthous terlihat lesu dan lemah. Ia jadi
sedikit hilang ingatan, serta lehernya selalu menoleh ke kiri dan kanan.
Itu semua akibat dari sakit stroke yang di deritanya, sehingga ia
terlihat seperti orang lumpuh. “Karena menderita stroke Mas Manthous
jadi nggak bisa ngapa-ngapain,” papar Utasih sambil mengelus pipi
suaminya.
Manthous sering meneteskan air mata kalau mengingat masa lalunya,
apalagi saat mendengarkan lagu-lagu ciptaannya. Meski Manthous mengalami
stroke yang membuat beberapa bagian tubuhnya lumpuh, akan tetapi ia
masih bisa berbicara dan berjalan. Pihak keluarga pun sudah berusaha
dengan segala cara untuk mengobati Manthous, namun hasilnya tetap nihil.
“Keluarga sudah bawa bapak berobat ke dokter, pengobatan alternatif,
bahkan dukun, namun semua tidak bisa nyembuhin penyakit bapak,” tutur
Utasih sambil meneteskan air mata.
Manthous sendiri lahir di desa Gunung Kidul, Yogyakarta, dan ia
adalah anak kedua dari enam bersaudara. Ia merupakan anak dari pasangan
(Alm) Wiryo Atmodjo dan Sumartinah. Kakak Manthous bernama Anti
Sugiartini, sedangkan keempat adiknya bernama Harjono, Yunianto, Sutomo,
dan Heru. Saat itu ayah Manthous bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri
Sipil) di Wonosari, Jawa Tengah, sedangkan ibunya sebagai ibu rumah
tangga. Sejak kecil Manthous sudah mempunyai bakat seni bermusik, dan
itu ia miliki secara otodidak (bakat alami).
Pada tahun 1957, Manthous kecil bersekolah di SR (Sekolah Rakyat)
Playen, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ketika SMP dan SMA pun ia bersekolah
di tempat yang sama, sehingga guru-guru di sekolah sangat mengenal sosok
laki-laki yang memiliki nama lengkap Anto Sugiartono. Saat Manthous
masih duduk di bangku SMP, ia sudah mendalami seni wayang. Bahkan
Manthous selalu menjadi perwakilan sekolah bila ada perlombaan seni
wayang.
Setiap pulang sekolah Manthous selalu bermain musik, dan itu ia
lakukan hampir setiap hari. Bahkan ia lebih mementingkan bermain musik
dari pada pendidikan, maka dari itu ia sering bolos sekolah demi bermain
musik. Karena mempunyai obsesi yang kuat untuk menjadi seniman besar,
maka pada tahun 1967 ia nekad pergi ke Jakarta. Saat Manthous memutuskan
untuk pergi ke Jakarta, ia rela tidak melanjutkan sekolahnya yang kala
itu masih duduk di bangku SMA.
Selama di Jakarta Manthous tinggal bersama kakaknya di daerah
Jatinegara, Jakarta Pusat. Selain tinggal di rumah kakaknya, terkadang
ia juga tinggal di rumah temannya. Saat pertama kali berada di Jakarta,
Manthous menjalani berbagai macam jenis pekerjaan. Ia pernah bekerja
sebagai kondektur bus, buruh pabrik sendok, montir bengkel motor, hingga
pengamen.
Memasuki tahun 1970 keberuntungan mulai berpihak kepada Manthous,
karena saat itu ia mulai bergabung dengan group musik bernama Bintang
Group Jakarta, pimpinan Budiman B.J. Dengan membawakan tembang-tembang
khas Jawa, Bintang Group Jakarta mendapatkan kontrak oleh Hotel Wisma
Nusantara, Jakarta. Saat itulah Manthous akhirnya menemukan tambatan
hatinya bernama Utasih, yang hingga kini menjadi istrinya. Manthous dan
Utasih menikah pada 29 Oktober 1972, kemudian mereka berdua di karunia
empat orang anak.
Dari tahun ke tahun Manthous menjalani karier bermusiknya, hingga
pada tahun 1992 ia membuat gagasan dengan membentuk group Campur Sari.
Sebenarnya group Campur Sari sudah ada jauh sebelum tahun 1992. Namun
saat itu Manthous sebagai pencetus musik Campur Sari dengan menggunakan
alat yang lebih modern. “Dahulu Campur Sari hanya memakai alat musik
tradisional saja, dan akhirnya Mas Manthous coba menggabungkan dengan
alat musik yang lebih modern,” jelas Utasih sambil memandang suaminya.
Memang berkat Manthous musik Campur Sari jadi lebih berwarna dan
tersohor.
Selain pendiri Campur Sari, Manthous adalah pencipta lagu yang
handal. Banyak karya-karya Manthous yang laku di pasaran, contohnya
seperti lagu Getuk yang dinyanyikan oleh Nurafni, lagu Jamilah yang
dinyanyikan oleh Jamal Mirdad, lagu Surga Neraka yang di populerkan oleh
Hetty koesendang, dan lagu Kangen yang di nyanyikan oleh penyanyi
dangdut Evi Tamala. Untuk satu lagu biasanya Manthous mendapatkan
bayaran Rp 1 juta. Sedangkan untuk sekali rekaman ia dapat meraup uang
sebesar Rp 200 juta sebagai royalti.
Dengan uang sebanyak itu, Manthous bisa dikatakan cukup sukses dalam
kariernya. Saat itu ia menjadi seorang yang kaya raya, hampir semua
keinginan yang ia impikan bisa tercapai. Saat itu Manthous bisa membuat
studio musik di Gunung Kidul dengan menghabiskan biaya sebesar hampir Rp
1 miliar. Kemudian ia bisa membeli empat buah mobil jenis Toyota
Corolla, Toyota Crown, Isuzu Panther, dan sebuah truck untuk mengangkut
alat musik. Selain itu ia juga bisa membangun dua rumah di daerah Gunung
Kidul dan satu rumah di Pamulang (rumah saat ini).
Namun masa kesuksesan seorang Manthous hanya bertahan selama sepuluh
tahun, hingga akhirnya ia menderita sakit stroke. Selain stroke,
Manthous juga menderita penyakit diabetes dan darah tinggi. “Karena
sakit itulah Mas Manthous jadi nggak bisa ngapa-ngapain lagi, hingga
akhirnya karir Mas Manthous mengalami penurunan,” tutur Utasih sedih.
Ketika mengalami stroke Manthous sempat tidak sadarkan diri, lalu ia
dibawa ke RS Bethesda, Yogyakarta. Di rumah sakit ia menjalani perawatan
selama dua minggu, dan menghabiskan dana sebesar Rp 12 juta.
Semenjak mengalami sakit stroke keadaan Manthous sangat
memprihatinkan. Ia hanya menghabiskan waktunya di rumah dengan ditemani
oleh istri, serta anak dan cucunya. Keluarga sudah berusaha membawa
Manthous berobat kemana-mana, namun hasilnya tetap tak ada perubahan.
Bahkan keluarga Manthous sering tertipu dengan orang-orang yang berusaha
ingin menyembuhkan sakitnya. “Karena ingin Mas Manthous segera sembuh,
kami sering tertipu orang dengan iming-iming pengobatan,” ungkap Utasih
geram. Sejak kejadian itu keluarga jadi tidak percaya kepada pengobatan
alternatif.
Sebagai seniman, Manthous sendiri tidak memiliki asuransi jiwa juga
asuransi kesehatan. Dahulu sebenarnya ia sempat memiliki asuransi jiwa,
namun karena tertipu Manthous pun memutuskan untuk tidak melanjutkan.
“Bapak pernah punya asuransi jiwa tapi karena di tipu, jadi bapak nggak
mau lagi pakai asuransi apapun,” terang Utasih.
Kini semua harta Manthous seperti rumah yang di Gunung Kidul dan
keempat mobilnya sudah habis terjual. Uangnya tentu saja untuk biaya
pengobatan dan menyambung hidup keluarga. Selama ini keluarga hanya
mengandalkan uang tabungan yang tersisa. Beruntung ketiga anaknya yang
bernama Tatut Dian Ambarwati (37), Ade Dian Chrismastuti (36), dan Denny
Dian Nawanina (35) sudah berumah tangga, sehingga bisa mengurangi beban
biaya. Biasanya ketiga anaknya yang sudah menikah ini sering membantu
untuk masalah keuangan. Sedangkan untuk Anindya Lanu Wardhani (22) saat
ini masih kuliah dan berdomisili di Yogyakarta, Jawa Tengah.
Akibat menderita stroke Manthous memang tidak berdaya lagi, bahkan
sebagai kepala rumah tangga ia sudah tidak bisa berbuat banyak untuk
keluarganya. Ia benar-benar menggantungkan hidup kepada istri dan
keempat anaknya. Untuk bantuan dari rekan-rekan artis juga tidak ada,
padahal sebagian dari mereka namanya pernah besar berkat Manthous.
Namun keluarga tidak pernah mempermasalahkan itu semua, karena
keluarga yakin meski dengan keterbatasan ekonomi mereka bisa
menyembuhkan Manthous. Beruntung Manthous memiliki istri dan anak-anak
yang dengan setia selalu merawat, serta menemani dirinya. Paling tidak
beban penderitaan Manthous sedikit berkurang, karena mendapatkan kasih
sayang yang tulus dari keluarga.
Sumber : http://www.matarama.co.id/news/manthous-campursari-meninggal-dunia.html